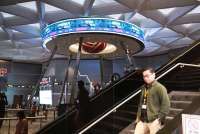Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Tidak semua emiten mau memanfaatkan kebijakan kelonggaran pembelian kembali saham (buyback) tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa di antaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).
Kedua emiten perbankan ini memiliki alasan tersendiri mengapa tidak bisa segera mengeksekusi buyback. Padahal, aksi buyback emiten perbankan diharapkan mampu mendongkrak kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terpuruk. Maklum, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang menjadi penggerak naik turunnya indeks.
Ketika dikonformasi mengenai masalah ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) beralasan tengah mengkaji secara komprehensif dan mendalam aksi buyback saham. "Yang jelas, aturan yang baru adalah peluang untuk hal tersebut (menstabilkan IHSG)," jelas Muhamad Ali, Sekertaris Perusahaan BBRI kepada KONTAN.
BBRI memang tengah mengkaji kebijakan tersebut. Pada dasarnya, manajemen memiliki kemampuan untuk mengeksekusi buyback saham tanpa RUPS. Hal ini bisa dilihat dari kuatnya kas internal yang dimiliki perusahaan.
Mengacu pada laporan keuangan BBRI per Juni 2013, tercatat ada saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya mencapai Rp 48,64 triliun. Sementara total modal yang ditempatkan dan disetor penuh BBRI sebanyak 24,67 miliar saham.
Dimintai konfirmasi terpisah, Gatot Suwondo selaku Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) bahkan menegaskan jika pihaknya tidak akan melakukan buyback.
Menurut Gatot, dana buyback bisa digunakan untuk penyaluran kredit sehingga bisa meningkatkan bottom line. "Penyaluran kredit resikonya Non-Performing Loan (NPL), tapi itu bisa ter-manage," imbuh Gatot.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kelonggaran buyback tanpa RUPS (sebanyak-banyaknya 20%) mampu menstabilkan pasar?
Pada kesempatan sebelumnya, Robinson Simbolon, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, mengatakan, buyback bukan hal yang mutlak untuk menstabilkan IHSG. Apalagi, fluktuasi IHSG belakangan ini sudah terputus dari fundamental emiten yang mencatat kinerja relatif bagus.
Tapi, IHSG itu sendiri merupakan indikator makro. Sementara emiten juga sangat rentan terhadap kondisi makro. Jika ada gangguan pada indikator makro maka pada akhirnya fundamental emiten juga akan terganggu. "Jadi, ini masalah berpacu mengambil kebijakan," tukas Robinson.
Sementara angka 20% itu sudah mempertimbangkan jumlah saham beredar (free float) di pasar modal lokal yang terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan negara lain.
Angka tersebut dinilai yang paling ideal untuk menjaga keseimbangan dan menjaga supaya transaksi di bursa tetap berjalan. "20% itu sudah besar di Indonesia, kalau lebih nanti pasar bisa kering," pungkas Robinson.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2013/04/01/2114170552.jpg)